404 - Halaman Tidak Ditemukan
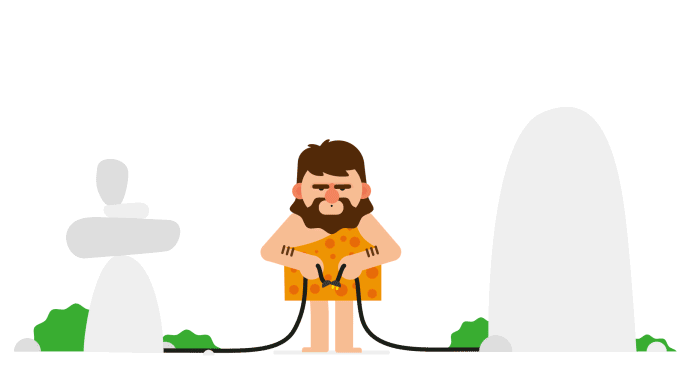
Maaf, halaman yang Anda cari tidak dapat ditemukan.
Silakan periksa kembali URL yang Anda masukkan, atau kembali ke halaman utama.
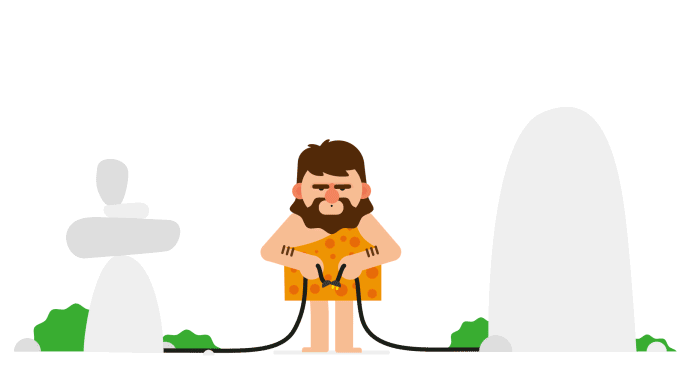
Maaf, halaman yang Anda cari tidak dapat ditemukan.
Silakan periksa kembali URL yang Anda masukkan, atau kembali ke halaman utama.
