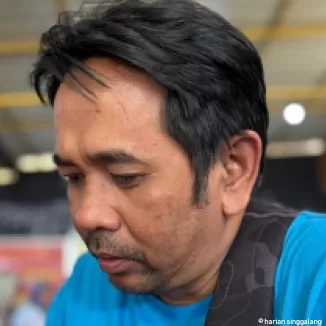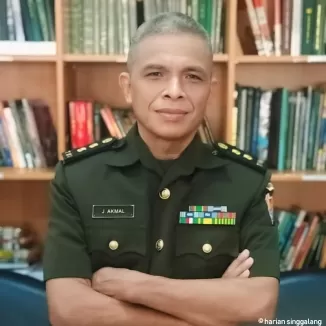Keengganan untuk melihat keberhasilan di luar diri sendiri ini mencerminkan semacam superioritas yang usang, yang seolah menganggap bahwa kita ini, Minang, masih di puncak. Klaim-klaim besar terus disuarakan, termasuk kebanggaan bahwa tiga dari empat tokoh bangsa adalah etnis Minang, berdasarkan foto lama yang menampilkan Hatta, Agus Salim, Sjahrir, dan Sukarno.
Apa benar, bangsa ini dibangun oleh segelintir orang saja? Di mana posisi pahlawan dari Jawa, Bali, Sunda, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah lainnya? Apakah mereka hanya pelengkap penderita yang bisa diabaikan begitu saja? Sejarah bangsa ini bukanlah hak eksklusif orang Minang, dan tak seharusnya kita menggenggam klaim itu seolah-olah bangsa ini terutang budi hanya kepada kita.
Kadang-kadang, saya berpikir, mungkin kita perlu melupakan identitas “urang awak” ini, setidaknya untuk sementara. Bayangkan, apa yang terjadi jika satu atau dua tahun kita berhenti menggunakan istilah “urang Minang” dan “urang awak.” Semua organisasi perantauan atas nama Minang, anggap saja dibekukan untuk sementara. Apakah kita akan segera jatuh miskin atau tiba-tiba hilang adat? Apakah kita langsung kehilangan arah dan nilai-nilai etika? Mungkin tidak. Malah, ini bisa menjadi langkah pembelajaran—mengungkapkan bahwa kita bisa menjadi bagian dari masyarakat yang harmonis tanpa harus terus mengusung keunggulan ini-itu. Bahkan, mungkin kita akan belajar menghargai perbedaan tanpa harus terus-menerus mengingatkan tentang apa yang kita anggap sebagai keunggulan Minang.
Mari kita bayangkan. Ketika kebanggaan ini kita lepaskan sementara, kita bisa kembali dengan kebanggaan yang lebih tulus dan realistis. Mungkin, saat kita berkumpul lagi, jargon “mambangkik batang tarandam” tak lagi kita lontarkan sekadar sebagai nostalgia murahan. Sebaliknya, jargon itu menjadi pengingat bahwa nilai yang sesungguhnya tak pernah tenggelam adalah nilai yang relevan. Nilai yang menghargai kontribusi orang lain, yang terbuka pada perubahan, dan yang tidak melihat masa lalu sebagai beban.Kita ini, orang Minang, perlu belajar rendah hati. Bukankah lebih baik kita melangkah bersama bangsa ini tanpa harus selalu mengedepankan klaim superioritas? Kebanggaan itu memang layak, tetapi kebanggaan yang tidak menginjak martabat pihak lain. Bangsa ini milik semua, dan setiap etnis di dalamnya punya kisah yang layak untuk dihormati, bukan semata bagian dari kebanggaan satu kelompok. Jika kebanggaan itu hanya membuat kita tertutup dari kenyataan, mungkin saatnya kita bertanya: apa yang sebenarnya ingin kita banggakan?