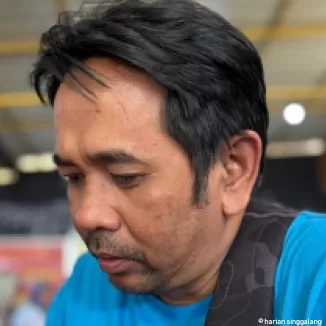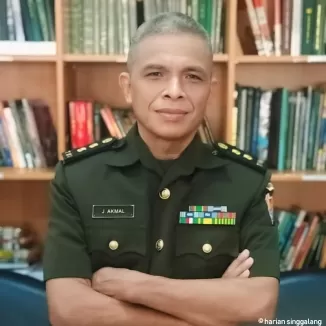Hal ini akan memunculkan banyak pertanyaan. Apakah ulama yang bersangkutan tidak “seulama” yang dibayangkan sehingga dukungannya tidak mempengaruhi kemenangan? Atau pernyataan lain adalah: apakah masyarakat sebebal itu sehingga tidak lagi mendengar ulama?
Kedua pertanyaan ini, menurut saya, sama-sama menimbulkan kerusakan. Sebagai manusia, ulama dapat saja kecewa terhadap kelompok tertentu karena merasa dukungannya tidak dihargai. Sejauh mana kekecewaan ini akan mempengaruhi interaksi ulama tersebut dengan kelompok masyarakat tertentu? Jika berdampak buruk tentu kita sayangkan, sebab itu akan menghalangi tugas-tugas mulia kenabian. Dapat pula muncul anggapan bahwa ulama atau organisasi ulama sudah kehilangan taji dan pengaruh, sehingga tidak didengar lagi suaranya. Senangkah hati kita dengan hadirnya anggapan ini?
Jika calon yang tidak didukung ulama memenangi Pilkada, bagaimana pula sikap dia terhadap ulama yang mendukung calon lain? Kita tentu tidak dapat pula mencegah ada rasa marah dan kecewa karena tidak didukung. Lalu siapa yang dapat menjamin bahwa rasa marah dan kecewa itu nanti tidak mempengaruhi kebijakan publiknya. Jika nanti pemenang menggunakan kewenangannya untuk mencegah ulama “kelompok sebelah” beraktifitas atau berkontribusi tentu ini akan melahirkan masalah baru nantinya. Apakah kondisi ini pantas diterima oleh orang Minang yang hidup di Ranah Minang?
Hal lain yang muncul adalah pembelahan sosial. Proses politik telah pasti membuat masyarakat terbelah, setidaknya pada beberapa sisi. Dukungan ulama terhadap satu calon menambah pembelahan yang sudah ada. Dalam perspektif persaingan politik, calon yang tidak didukung oleh ulama artinya berada pada pihak yang berseberangan dengan ulama tersebut. Makna lain adalah calon yang tidak didukung bukan lah calon pemimpin yang saleh-amanah, dan tidak terlalu berpihak pada kepentingan umat. Didukung ulama dianggap calon yang baik, tidak didukung dianggap calon yang tidak baik.
Pertanyaannya, apakah itu layak terjadi di ranah minang dan kepada orang-orang minang hanya akibat Pilkada? Apakah satu calon sebegitu bertentangan dengan umat dan agama, sehingga seorang atau sekolompok ulama memberikan dukungan kepada calon lainnya? Apakah pendukungnya juga dianggap sebagai kelompok yang tidak (terlalu) memihak pada kepentingan Islam oleh ulama atau kelompok ulama yang memberikan rekomendasi? Bagaimana memperbaiki pembelahan akibat dukung mendukung dari kalangan ulama ini?
Isu lainnya adalah bagaimana dengan dukungan dua ulama atau dua kelompok ulama pada dua calon yang berbeda? Dukungan kelompok mana yang lebih mewakili unsur kenabian dalam hal ini? Bagaimana menjelaskan ini kepada masyarakat umum?Pertanyaan lainnya adalah, jika seorang ulama mendukung satu calon secara terbuka, dan kemudian si calon melakukan kesalahan -seperti korupsi atau melanggar etik- bagaimana ulama tersebut akan bertanggung jawab? Bagaimana jika ulama itu tidak menetap di Sumatera Barat? Bagaimana ulama dan kelompok ulama menjawab pertanyaan sumbang publik yang akan diarahkan kepada mereka?
Pertanyaan-pertanyaan di atas sulit menjawabnya. Terlihat lebih menghasilkan masalah ketimbang jawaban. Saya melihat bahwa kita dan calon-calon yang ada pada dasarnya hidup dalam kesetujuan bersama terhadap filsafah hidup yang ada, yaitu ABS-SBK (adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah). Terlebih lagi ABS-SBK itu sudah diakui secara resmi dalam UU no 17/2022 tentang Pemprov Sumatera Barat. Jika ada perbedaan, tentu tidak pada aspek yang mendasar dan ideologis. (***)