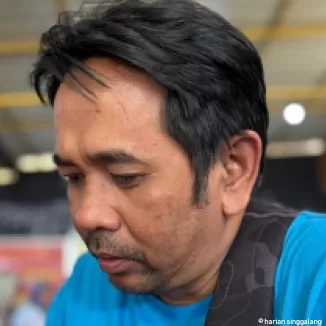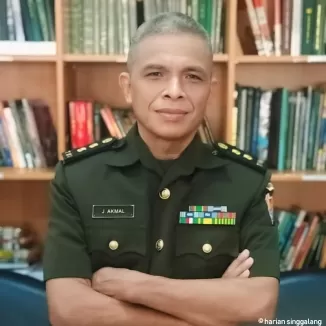Datang ke istana gubernur ini sungguh bukan hal yang menyenangkan bagi saya. Tetapi karena saya manusia bukan hewan, saya datang juga. Manusia berbeda dari hewan lain dalam banyak hal. Salah satunya adalah, ia bersedia terlibat dalam kegiatan yang tidak menyenangkan, karena kegiatan tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.
Tak ada yang saya harapkan dari kedekatan dengan penguasa seperti ini. Apakah akan menumbuh-suburkan kreativitas atau menumbuh-suburkan ke’ongeh’an. Bagi saya, di luar semua asumsi itu, ke istana hari ini untuk menunjukkan hormat saya pada HET, pada karyanya dan nafas panjangnya dalam menulis.
Cerpen-cerpen HET bagi saya cukup menyengat. Dulu, sewaktu kami masih berlangganan koran, saya menunggu akhir pekan dengan hati riang, berharap ada cerpen dari Sumatera Barat akan muncul di koran nasional. Membaca cerpen bagi saya adalah pupuk bagi pikiran yang liar tak berketentuan. Dan cerpen HET lah yang paling saya tunggu, di samping tulisan AA Navis, Wisran Hadi, Gus Tf, Darman Moenir, Yusrizal KW, Pinto Anugrah, Esha, Heru, Romi, Yetti Aka, dll. Akh, satu masa yang tak akan bisa mungkin terulang. Mereka, para penulis Sumatera Barat itu, semua sudah sekarat. Mereka sudah berhenti, sudah pergi, lelah digulung nasib masing-masing. Mereka terbata-bata mengeja kata yang semakin susah dikendalikan. Kekuasaan di luar diri datang semena-mena, tak mampu ditahan tak kuasa untuk dilawan. Koran pun sekarang tak lagi terbit, kecuali satu dua. Akhir pekan berubah jadi ruang gelap, tak beda dengan hari lainnya, di mana orang tak ada waktu lagi memikirkan karya sastra, menulis puisi dan menata kepahitan hidup dalam narasi sastrawi.
Dalam suasana seperti ini, merayakan kepenulisan HET adalah momen yang membahagiakan. Ongok-ongok dalam boncah, tetap bernafas dalam lumpur, tidak apa. Kita perlu terus bersukur karena kita masih punya seseorang seperti dia. Karya HTE seperti lukisan. Lukisan yang menonjolkan nilai yang sedang dia perjuangkan sebagai pengarang.
Perempuan ringkih itu ingin berbaring, melepas lelah dipukul rindunya yang terpendam. Akan tetapi kamar itu mirip gudang yang sudah lama ditinggal pemiliknya. Semuanya berantakan dan penuh debu. Tumpukan buku, kertas-kertas coretan, bungkus rokok, koran di segala sudut, kasur lecet yang terlipat, gelas-gelas bekas kopi, sendal butut, dan setumpuk pakaian kotor. Poster-poster terkelupas di dinding yang lembap dirangkai jelaga dan jaring laba-laba yang sesekali bergerak lemah ditiup angin dari lubang udara. Di balik pintu, bergelantungan celana jin robek dan jaket bau keringat petualang.
Tanpa sempat mengusik kecentang-perenangan itu, Anisah terduduk di samping lipatan kasur tanpa alas, merenungkan wajah putra kebanggaannya itu. (Anak Panah)
Engku Nawar mencoba bersabar. Baginya waktu terasa berjalan lambat. Ia merasa sesak duduk beramai-ramai di ruang tamu yang sempit itu. Ia lalu berdiri, keluar dan mencari bangku-bangku beton di taman halaman samping rumah dinas Wali Kota itu bersama Sarini yang mengikutinya dari belakang. Ia amat berharap Wali Kota yang muda dan gagah itu muncul menemuinya di tempat terpisah dari tamu-tamu lain. Meski batuk-batuk dan dilarang cucunya, ia masih mencoba merokok, menghilangkan rasa jenuh. Baju koko terbaik yang dipakainya terasa sangat tipis dari sentuhan angin malam terhadap tubuhnya yang telah ringkih. Ia mempererat belitan sarung di lehernya. Diam dengan pikirannya yang menerawang. Dan, Sarini hanya bisa mengunyah permen karet di samping kakeknya sambil mengasuh harapan-harapannya untuk diterima Wali Kota menjadi pegawai honorer. (Arwana)Lelaki setengah umur itu memarkir gerobak kecilnya di bawah pokok akasia tak jauh setelah membelok ke kanan tanpa membangunkan anjing betina hitam kurus yang terlelap di atas bundelan-bundelan dalam gerobak itu. Ia menepi ke pinggir sungai yang penuh sampah plastik, lalu kencing begitu saja. Ia tersentak kaget ketika mendengar anjingnya terkaing. Seorang bocah perempuan ingusan yang memegang krincingan dari kumpulan tutup botol minuman telah melempari anjing itu. Lelaki itu berkacak pinggang, menatap bocah perempuan ingusan itu dengan tajam. Bocah perempuan ingusan itu balas menantang sambil juga berkacak pinggang. Anjing betina hitam kurus itu mengendus-endus di belakang tuannya, seperti minta pembelaan.
Lelaki itu kembali mendorong gerobak kecilnya dengan bunyi kricit- kricit roda besi kekurangan gemuk. Anjing betina kurus berwarna hitam itu kembali melompat ke atas gerobak, bergelung dalam posisi semula. Bocah perempuan yang memegang krincingan itu mengikuti dari belakang dalam jarak sepuluh meteran. Bayangan jalan layang tol dalam kota, melindungi tiga makhluk itu dari sengatan matahari. Sementara lalu lintas semakin padat, udara semakin pepat berdebu. (Persahabatan Sunyi).
HET mengangkat realitas ke hadapan kita dalam bentuk karya sastra—yang sepahit apa-pun hidup itu— ia bisa kita kunyah-kunyah sambil berselonjor di atas kasur empuk. Bisa juga digunakan oleh pemerintah untuk menundukkan perlawanan orang-orang miskin yang tiap tahun makin bertambah. Seolah kemiskinan itu adalah bayi ‘haram’ hasil perselingkuhan ibu rakyat dan ayah pejabat. *