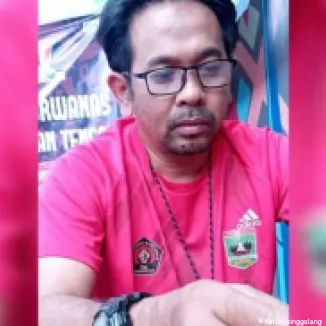Komunikasi pembangunan adalah alat vital dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Namun, seiring berjalannya waktu, cara kita berkomunikasi tentang pembangunan telah berubah. Komunikasi pembangunan itu sendiri diartikan sebagai aktivitas manusia yang membawa informasi tentang ide, benda, tempat, orang dan kebijakan melalui mana manusia memahami orang lain dan juga dipahami oleh orang lain (Cangara, 2020). Jadi bukan sebatas penyampaian informasi, komunikasi pembangunan kini lebih menyebutkan unsur masyarakat dalam prosesnya. Dan proses komunikasi pembangunan ini setiap tahunnya juga mengalami perkembangan di Indonesia sendiri, dari yang awalnya satu arah, kini berkembang menjadi lebih inklusif dan interaktif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.
Dilihat dari sejarahnya, komunikasi pembangunan ini didominasi oleh model top-down, di mana pemerintah berperan sebagai pengirim pesan, sementara masyarakat menjadi penerima pasif. Model komunikasi semacam ini sangat mengandalkan media massa tradisional seperti radio, televisi, dan surat kabar untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan atau proyek pembangunan yang sedang berjalan. Pada tahun 1970-an, kita melihat model komunikasi ini diterapkan dalam berbagai program pembangunan seperti REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Proyek ini berfokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran yang mengandalkan komunikasi untuk memberitahukan masyarakat tentang program-program pemerintah. Namun, meskipun informasi tersebar luas, masyarakat sering kali hanya tahu tentang kebijakan atau proyek tanpa benar-benar terlibat dalam proses perencanaan atau pelaksanaan.
Memasuki tahun 1980-an, para ahli komunikasi mulai menyadari bahwa pendekatan top-down ini tidak cukup efektif. Komunikasi pembangunan bukan hanya soal memberi tahu masyarakat, tetapi lebih tentang mendengarkan mereka, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan berdialog dengan masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai model bottom-up, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk kebijakan dan pelaksanaan proyek. Di Indonesia, perubahan ini mulai terlihat dalam berbagai proyek yang melibatkan masyarakat lokal. Misalnya, dalam pengembangan Pembangunan Desa, masyarakat mulai diajak untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang apa yang mereka butuhkan, bagaimana cara mereka ingin pembangunan dilakukan, dan apa yang harus diprioritaskan. Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak hanya memberi informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan kebutuhan mereka, yang membuat pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi setempat.
Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi digital, khususnya internet dan media sosial, telah membawa perubahan besar dalam cara komunikasi pembangunan dilakukan. Jika dahulu media massa menjadi saluran utama informasi, kini ada media sosial, aplikasi mobile, dan website partisipatif menjadi sarana utama untuk menjangkau masyarakat. Era digital memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, langsung, dan dua arah, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memberikan masukan secara real-time. Kita melihat bagaimana penerapan komunikasi pembangunan berbasis digital pada proyek Jalan Tol Trans-Jawa. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memanfaatkan platform media sosial dan situs web untuk menginformasikan perkembangan proyek kepada masyarakat dan untuk mengumpulkan umpan balik dari mereka. Masyarakat yang merasa terdampak oleh proyek jalan tol, misalnya yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan, bisa langsung mengungkapkan kekhawatiran mereka, seperti tentang polusi atau dampak terhadap lahan pertanian, melalui saluran komunikasi yang disediakan.
Tantangan dalam Partisipasi Masyarakat
Meskipun era digital telah mempermudah proses komunikasi dan partisipasi masyarakat, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya ketimpangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat di kota besar cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap internet dan teknologi, sementara di pedesaan, banyak yang belum terbiasa atau tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat digital.
Selain itu, meskipun teknologi dapat mempercepat penyebaran informasi, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dipahami atau diterima oleh pengambil keputusan. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan mekanisme partisipasi yang tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga bisa mencakup bentuk interaksi lain yang lebih inklusif, seperti pertemuan tatap muka atau forum komunitas.
Partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan bukan sekadar memberikan mereka informasi, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dalam kerangka ini, komunikasi menjadi dua arah, di mana tidak hanya pemerintah yang memberikan informasi, tetapi masyarakat juga memberikan masukan, kritik, dan solusi yang dapat memperbaiki kualitas kebijakan yang diterapkan.
Di beberapa proyek pembangunan infrastruktur, seperti proyek pembebasan tanah untuk jalan tol, komunikasi pembangunan telah melibatkan masyarakat secara lebih aktif. Pemerintah tidak hanya memberikan informasi mengenai pembebasan lahan, tetapi juga menerima keluhan dan saran dari masyarakat yang merasa terdampak. Ini membuka ruang bagi pengambilan keputusan yang lebih berkeadilan, di mana setiap pihak yang terdampak bisa mendapatkan kompensasi yang adil dan solusi yang sesuai.