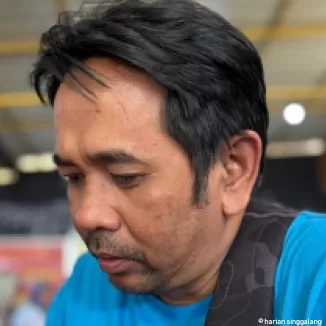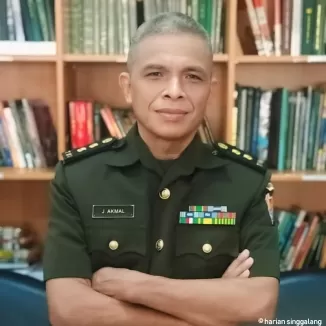Menjadi orang Minang tentu saja menyiratkan kebanggaan tersendiri. Bagaimana tidak, sejarah telah mencatat nama-nama besar dari ranah kita yang mewarnai perjalanan bangsa.
Di masa perjuangan kemerdekaan, nama Hatta, Agus Salim, dan Sjahrir pernah menggemakan nama Minang dalam sejarah nasional.
Tidak berlebihan bila kita merasa pernah berada di puncak kejayaan, bahkan, mungkin, merasa sedikit lebih unggul dari etnis lain.
Tapi, di sinilah awal dari masalah ini: kebanggaan yang dulu menjadi simbol prestasi kolektif, kini seakan berubah menjadi semacam “overproud,” kebanggaan berlebihan yang menyamarkan kemampuan kita untuk mengakui peran orang lain.
Mungkin sudah tiba waktunya kita sedikit berkaca—di mana posisi kita sebenarnya di tengah bangsa yang semakin bergerak ke depan ini?
Kita mungkin pernah mendominasi narasi nasional di berbagai bidang—politik, pendidikan, kewirausahaan, bahkan diplomasi—seolah-olah kejayaan itu adalah hak istimewa yang selalu diwariskan. Tetapi, lihatlah realitas kini: bangsa ini sudah jauh lebih maju dan inklusif.Kesenjangan semakin berkurang, dan setiap daerah punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Ya, dominasi Minang dalam beberapa hal kini semakin menipis, bahkan cenderung bergeser ke proporsi yang lebih seimbang. Tak ada yang salah dalam hal ini; malah seharusnya kita bersyukur. Bukankah ini mencerminkan keberhasilan bangsa dalam menyediakan akses bagi semua lapisan masyarakat.
Namun, sebagian kita masih enggan melihat ke arah tersebut. Ironisnya, kita sering terjebak dalam glorifikasi masa lalu yang seakan-akan hidup untuk selama-lamanya. “Mambangkik batang tarandam”—ini jargon yang terus didengungkan di setiap pertemuan Minang, padahal siapa yang sedang benar-benar berusaha mengangkatnya? Seolah batang terendam itu adalah relik kejayaan yang tak lekang waktu, dan kita hanya perlu menyerukannya untuk kembali ke permukaan.
Tapi, mungkin kita perlu bertanya: apa yang sedang kita coba angkat? Ide yang relevan dengan zaman, atau sekadar nostalgia?
Di era digital saat ini, kebanggaan berlebihan itu pun semakin kentara, bahkan semakin mengusik. Ketika ada berita tentang kuliner daerah lain, kita tak ragu menyanggahnya dengan klaim, “Ya, enak sih, tapi masih kalah dengan makanan Minang.” Atau, saat orang mengagumi alam daerah lain, hampir pasti kita berkomentar, “Tapi tetap lebih indah Ranah Minang.” Apakah ini bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya kita? Atau sekadar penolakan untuk mengakui bahwa keindahan dan kelezatan itu bukan milik kita seorang? Sejujurnya, berapa lama kita akan terus memaksakan standar ranah Minang pada seluruh Nusantara.
Fenomena kebanggaan yang membutakan ini bahkan pernah sampai pada kasus nyata yang, tanpa ragu saya katakan, sangat memalukan. Beberapa hari lalu, RM Padang dirazia karena menjual makanannya di harga yang murah. Lalu muncul bantah membantah, bahkan melibatkan sebuah organisasi rantau yang berbicara tentang sticker keaslian cita rasa Minang. Otentik bahasa ketua hariannya. Bayangkan, di era globalisasi ini, ada yang masih merasa perlu mengatur standar masakan sesuai keasliannya. Padahal, restoran Minang di berbagai kota sering kali beradaptasi dengan selera lokal, dan itulah kunci suksesnya. Apakah perlu semua hidangan Padang di seluruh Nusantara disesuaikan agar memenuhi standar Sumatra Barat? Atau, mungkin saja kita lupa, bahwa masakan bukan soal absolut, melainkan soal adaptasi.